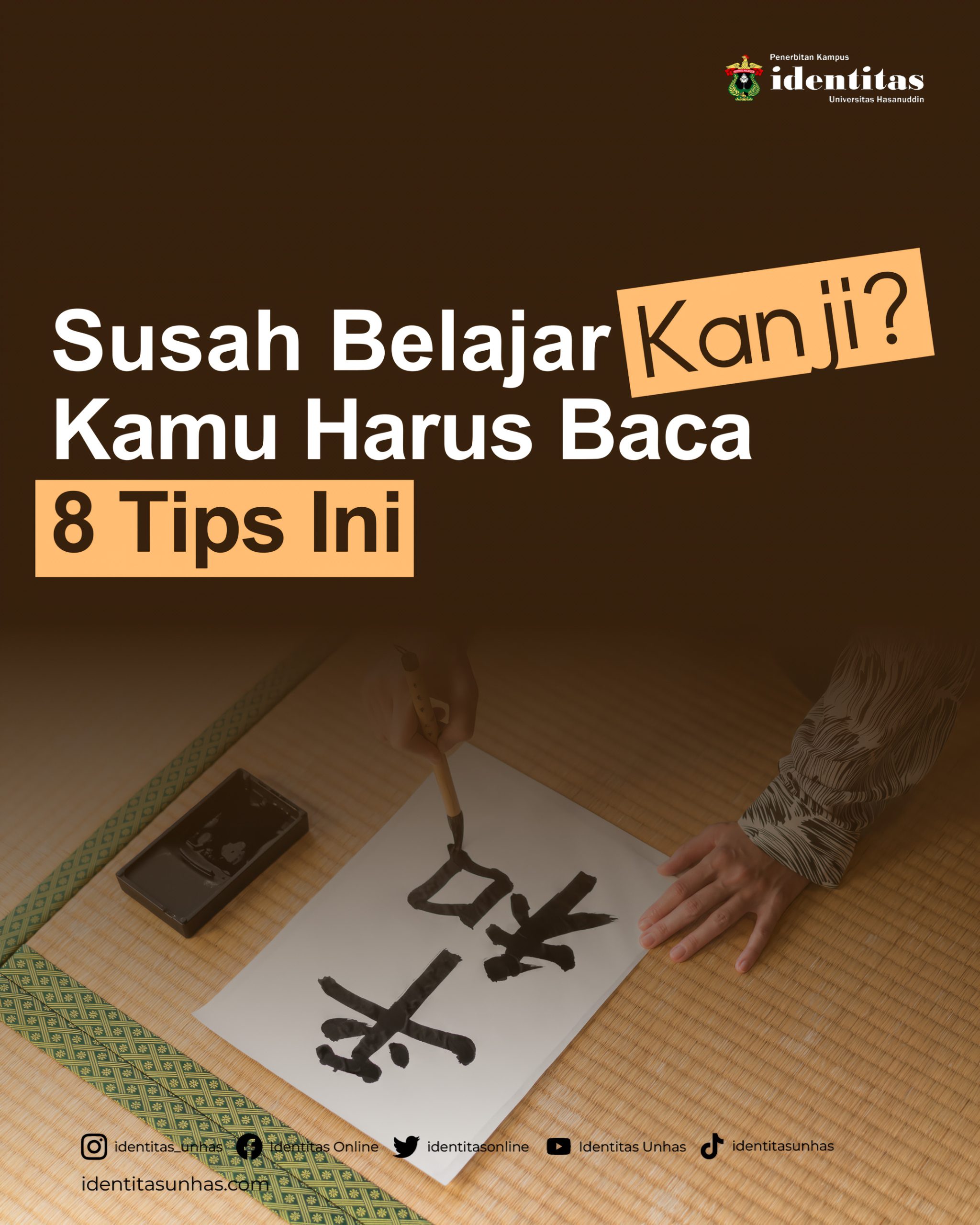“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Sebagai negera dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia tak terlepas juga dari banyaknya jumlah masyarakat miskin. Salah satu kelompok masyarakat yang mengalami persentase kemiskinan yang tinggi ialah nelayan. Berdasarkan data penelitian Anwar dan Yuni (2019) terdapat 14,58 juta dari 16,2 juta nelayan yang berada dibawah garis kemiskinan.
Nelayan di daerah Kepulauan Spermonde, Pulau Kodingareng salah satu contohnya, aktivitas tambang pasir sejak 2020 lalu untuk reklamasi pembangunan Makassar New Port mempengaruhi ruang hidup serta ekonomi masyarakat sekitar.
Berangkat dari hal tersebut, Dosen Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Unhas, Andi Kurniawati SH MH, serta mahasiswa Departemen Hukum Perdata Hukum Rizkal Nur dan Dyno Thiodores melakukan penelitian tentang dampak pertambangan pasir laut terhadap hak asasi nelayan di Kawasan Spermonde.
Penelitian yang diterbitkan Fakultas Hukum Univeristas Mulawarwan dalam Mulawarman Law Review ini menggunakan data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan, pengamatan langsung, kajian pustaka, dan wawancara dengan penduduk di Kepulauan Spermonde.
Rizkal ikut meneliti karena isu pertambangan pasir di Kepulauan Spermonde telah tersebar secara nasional. Selain itu, akan berdampak buruk terhadap laut dan nelayan sekitar. “Kami mengangkat sudut hak asasi nelayan karena memang sudah dijamin oleh undang-undang,” ujarnya, Rabu (29/03).
Ia melanjutkan, saat ini penambangan pasir telah dihentikan, akan tetapi beberapa waktu lalu muncul isu perihal akan dilakukannya kembali penambangan untuk memenuhi kebutuhan reklamasi kawasan Center Point of Indonesia (CPI).
Ekosistem laut akibat pengerukan kapal tambang menyebabkan air laut menjadi keruh. Kekeruhan ini menyulitkan nelayan mendapatkan ikan, sehingga mengakibatkan penurunan jumlah tangkapan ikan.
“Aktivitas tambang pasir ini akan mencemari laut sehingga dapat merusak terumbu karang yang menjadi tempat hidup dan berkembang biak ikan, juga dapat memicu abrasi di kawasan pesisir,” tambah mahasiswa angkatan 2019 ini.
Selain menggunakan data numerik, peneliti juga menggunakan data dari wawancara dengan masyarakat. Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya polarisasi antara masyarakat terhadap pertambangan pasir laut.
“Masyarakat yang menolak sudah tau dan merasakan dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan pasir tersebut, seperti hasil tangkapan yang berkurang, perusakan alam, dan lain-lain,” ucap Rizkal.
Sebenarnya terdapat peraturan pemerintah yang mengatur dan memayungi nelayan dan masyarakat pesisir. Terlebih lagi dalam penambangan diperlukan berbagai jenis izin, seperti Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), persetujuan masyarakat yang akan terdampak, dan lain-lain. Namun, penerapan di lapangan masih jauh dari yang seharusnya.
“Kalau dari sisi produk hukumnya (undang-undang) sendiri sudah dapat menjamin hak-hak nelayan, tetapi yang menjadi masalah adalah dalam tingkat implementasi atau penerapannya di lapangan masih kurang,” ucap Rizkal.
Data numerik tentang hasil tangkapan sebelum dan setelah tambang pasir laut dilakukan menunjukkan adanya penurunan tangkapan yang signifikan sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat, bahkan ada beberapa jenis ikan yang tidak dapat ditemukan di kawasan yang sama setelah pertambangan pasir.
“Hal ini membuat banyak nelayan yang berpindah profesi, sampai harus menggadaikan harta bendanya untuk dapat tetap bertahan hidup,” tambahnya.
Setelah mengalami kerugian, nelayan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan maupun pemerintah. “Yang paling mungkin dilakukan dalam kasus dimana kerugian telah terjadi adalah pencabutan izin penambangan oleh pemerintah agar kerugian yang muncul tidak semakin parah,” ucap mahasiswa tidak jelas tersebut.
Rizkal berharap, pemerintah lebih memperhatikan hak-hak nelayan dalam melakukan pembangunan, terlebih hal ini telah diatur oleh undang-undang.
Selain itu, ia juga memaparkan bahwa belajar dari beberapa kasus pertambangan pasir untuk reklamasi sebelumnya seperti CPI dan Makassar New Port, isu-isu seperti pulau Lae-Lae perlu diperhatikan berbagai pihak karena pada akhirnya jika dilakukan dengan metode sebelumnya akan berakhir merugikan masyarakat luas.
M Ridwan