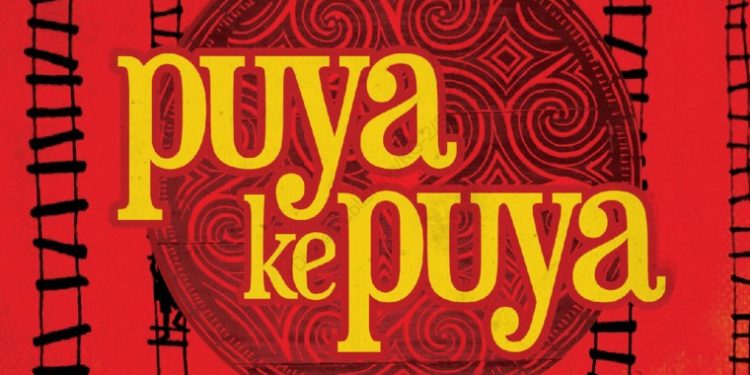“Untung ada yang menangkap tangannya. Parangnya tak jadi menebas. Kepala Allu Ralla tidak jadi lepas. Maut masih baik hati.”
Pernahkah kamu menyaksikan kematian dan membayangkan seperti apa kehidupan setelahnya? Apakah berhenti saat itu juga atau malah baru akan dimulai di suatu tempat yang baru?
Pertanyaan ini menjadi inti cerita Puya ke Puya karya Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Hasanuddin (Unhas), Faisal Oddang. Novel tersebut mengangkat kehidupan masyarakat Toraja beeserta kepercayan dan adat yang menyertai kehidupan dan kematian.
Cerita bermula saat Rante Ralla, bangsawan sekaligus pemimpin tongkonan Kete’ wafat. Kematian itu tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga awal dari berbagai konflik besar di keluarga yang ditinggalkan.
Sebagai anak sulung, Allu Ralla memikul tanggung jawab untuk melaksanakan upacara rambu solo, tradisi pemakaman mewah masyarakat Toraja yang juga menjadi simbol kehormatan keluarga.
Semakin banyak kerbau dan babi yang disembelih, semakin tinggi pula derajat arwah di alam Puya, tempat roh menuju setelah kematian. Namun, semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Dari sinilah beban Allu Ralla dimulai. Ia dihadapkan pada dilema antara menjaga nama baik keluarga dan menanggung beratnya biaya adat.
Dalam pikirannya, ia sadar, kehidupan keluarganya akan terpuruk jika semua harta habis untuk upacara. Namun, di sisi lain, menolak tradisi berarti menodai kehormatan leluhur dan mempermalukan nama Ralla di mata masyarakat.
Puya ke Puya menggambarkan bagaimana adat yang sakral bisa menjadi sumber konflik, bukan karena salah satu pihak ingin berbuat jahat, tetapi karena semua merasa benar dalam caranya masing-masing.
Di tengah tekanan itu, muncul sosok Tina Ralla, istri mendiang Rante Ralla. Ia kini menjadi to balu, janda yang harus menanggung beban sosial dan ekonomi keluarga.
Tina menyaksikan bagaimana anaknya berjuang keras memenuhi tuntutan adat itu, sementara ia sendiri hanya bisa diam, menahan perih dan pasrah pada nasib.
Cerita dalam Puya ke Puya tidak disampaikan dengan urutan waktu yang lurus. Kisahnya berpindah-pindah antara masa lalu dan masa kini, antara dunia orang hidup dan dunia arwah.
Kadang kita berada di pikiran Allu Ralla, lalu tiba-tiba berpindah ke kenangan ambe atau suara arwahnya yang memandang dari dunia lain. Alur yang terasa melompat-lompat ini justru membuat pembaca ikut merasakan ketegangan batin para tokohnya antara kenyataan dengan hal-hal tak kasat mata.
Novel yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2015 seolah-olah mengaburkan batas antara hidup dan mati.
Dalam kepercayaan Toraja, roh seseorang belum benar-benar pergi sebelum seluruh rangkaian upacara selesai. Oleh karena itu, dunia orang hidup dan dunia roh saling berdekatan, bahkan terasa saling menatap.
Di titik inilah novel peraih penghargaan Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2014 ini, tak lagi sekadar berkisah tentang kematian, melainkan tentang kehidupan yang terus berlanjut setelahnya.
Dalam novel tersebut, Faisal Oddang memperlihatkan, kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi bagian dari siklus yang harus dijalani. Setiap tokoh berjuang menemukan makna di antara adat, kehilangan, dan keyakinan mereka pada dunia arwah.
Melalui kisah keluarga Ralla, pembaca diajak menelusuri nilai-nilai hidup dalam masyarakat Toraja yaitu tentang kehormatan, pengorbanan, dan cinta yang melampaui kematian.
Semakin jauh membaca, semakin terasa bahwa konflik terbesar dalam hidup manusia bukan antara benar atau salah, melainkan antara tradisi dan kenyataan serta warisan leluhur dan tuntutan hidup yang kian modern.
Puya ke Puya bukan hanya kisah tentang kematian, melainkan kisah tentang bagaimana manusia menghadapi kehidupan setelah kehilangan.
Ia mengajak kita bertanya, sejauh mana kita siap menanggung beban tradisi demi menjaga nama baik keluarga? Ataukah justru perlu keberanian untuk melangkah dan menemukan makna baru tentang kehormatan?
Fitriani Andini