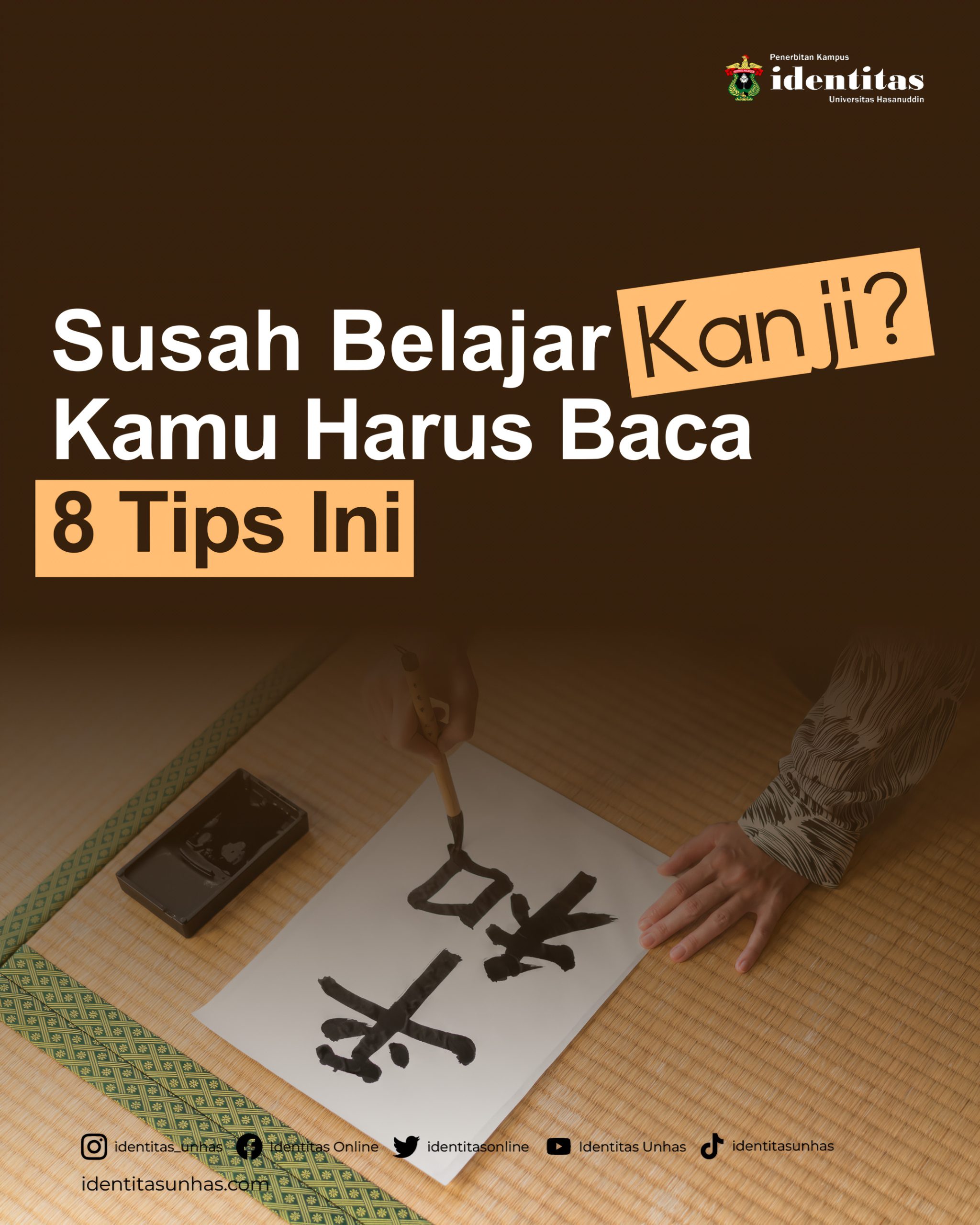Masalah lingkungan hidup adalah masalah kita semua. Seringkali kita mendengar berbagai isu lingkungan yang beredar di tengah masyarakat seperti kekeringan, kebakaran hutan, banjir, dan lain sebagainya. Hal itu dilatarbelakangi oleh dampak perubahan iklim. Apabila hari ini kita meyakini bahwa dampak tersebut menggambarkan betapa buruknya kondisi lingkungan kita saat ini, pada realitanya ternyata jauh lebih buruk dan memprihatinkan.
Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa akibat perubahan iklim diproyeksikan akan menjadi penyebab penurunan produksi pangan dunia sekitar 1-7 persen hingga 2060. Jika hal tersebut tidak segera diantisipasi, maka diperkirakan sekitar 20 persen penduduk dunia berisiko kelaparan.
Perubahan iklim didefinisikan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor alami yang dipicu oleh berbagai aktivitas manusia atau industri yang mampu menghasilkan emisi gas rumah kaca. Saat ini, upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sangat perlu diapresiasi.
Indonesia telah menunjukkan komitmennya pada mata dunia untuk berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen secara mandiri dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030 melalui NDC (Nationally Determined Contributions). Namun dibalik keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut, ada hal yang perlu kita garis bawahi bersama.
Bagaimana bisa kita berbicara soal komitmen, berbicara soal dukungan internasional, jika pada realitanya pemahaman masyarakat kita tentang emisi gas rumah kaca beserta dampaknya ternyata masih sangat minim? Bagaimana bisa kita yakin pada penerapan energi hijau ditengah masyarakat jika pada realitanya praktik-praktik yang terjadi di sektor industri masih buruk dan dinormalisasi?
Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih jauh, maka pondasi inilah yang seharusnya diperbaiki dan dibenarkan terlebih dahulu. Karena segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendegradasi dampak perubahan iklim, tidak akan bisa berjalan dan selaras tanpa pengetahuan yang baik serta praktik yang seimbang oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ada satu terminologi yang mungkin sudah bosan kita dengar berkali-kali, yaitu Net Zero Emission. Pada intinya, Net Zero Emission adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyeimbangkan antara emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh suatu entitas dengan jumlah emisi yang dihilangkan di atmosfer.
Jika kita berkaca pada terminologi tersebut, pertanyaan yang sekiranya muncul di hati dan pikiran kita adalah bagaimana suatu negara dapat dikatakan sebagai negara Net Zero Emission? Dan sebenarnya dimana posisi kita saat ini? Jawaban pragmatisnya adalah ketika negara kita telah mampu menggantikan bahan bakar fosil dan sejenisnya dengan sumber energi terbarukan.
Saat ini, berdasarkan informasi dari Environmental Performance Index (EPI), Indonesia berada di posisi menengah dengan skor yang mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan energi terbarukan.
Artinya, butuh sebuah lonjakan yang luar biasa dalam proses transisi energi sehingga negara kita bisa lolos dari posisi kelas menengah menjadi negara kelas atas. Akan tetapi, yang menjadi tantangan besar kita saat ini adalah apakah kita mampu naik kelas dari posisi menengah ke posisi atas?
Secara teori peluang ini sangat terbuka jika melihat betapa melimpahnya kekayaan alam Indonesia khususnya pada sektor kelapa sawit. Namun satu hal yang pasti, pemanfaatan kekayaan alam tersebut sangat bergantung tentang bagaimana kita mampu mengetahui potensi, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh negara kita saat ini.
Berbicara mengenai potensi dan peluang, secara umum keadaan geografis dan berbagai faktor lainnya Indonesia memiliki keunggulan yang jauh lebih besar dari negara lain dalam memanfaatkan kekayaan alam. Namun yang menjadi tantangan terbesar di negara kita hari ini adalah rendahnya produktivitas dan minimnya inovasi.
Selama produktivitas kita masih rendah dan inovasi kita masih minim, maka target Net Zero Emission hanyalah sebatas retorika. Menurut informasi yang diperoleh dari OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), program pendidikan di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri yang pada akhirnya menyebabkan kekurangan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas.
Oleh karena itu, disinilah peran pemerintah khususnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengambil langkah strategis. Rekomendasi yang ditawarkan dan sebaiknya diterapkan oleh BPDPKS adalah menaikkan dana anggaran PDB minimal dari 0,3 persen menjadi 0,5 persen untuk mendukung penelitian dan pengembangan inovasi sebagai langkah awal keseriusan pemerintah.
Di mana selama ini berdasarkan hasil riset UNESCO Institute for Statistics pada 2021, Indonesia hanya menghabiskan sekitar 0,25 persen dari PDB untuk riset dan pengembangan, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN yang mencapai 1 persen dari PDB. Hal ini berdampak pada kemampuan negara untuk menghasilkan inovasi baru, dan akhirnya juga berbanding lurus pada produktivitas.
Sebagai kesimpulan, Net Zero Emission akan bisa tercapai apabila ekspansi energi terbarukan kita telah mampu menyaingi produktivitas energi fosil dan sejenisnya. Saat ini, inovasi yang tengah dikembangkan dan didukung oleh negara kita adalah biodiesel dari kelapa sawit.
Melalui peningkatan anggaran dalam bidang riset dan inovasi tersebut, harapannya terjadi peningkatan produktivitas yang mampu menjadi solusi dari Net Zero Emission. Akhirnya, BPDPKS menciptakan kebijakan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Fahmi Alfarabi
Mahasiswa Departemen Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian
Ketua Umum KM PILAR Periode 2022-2023