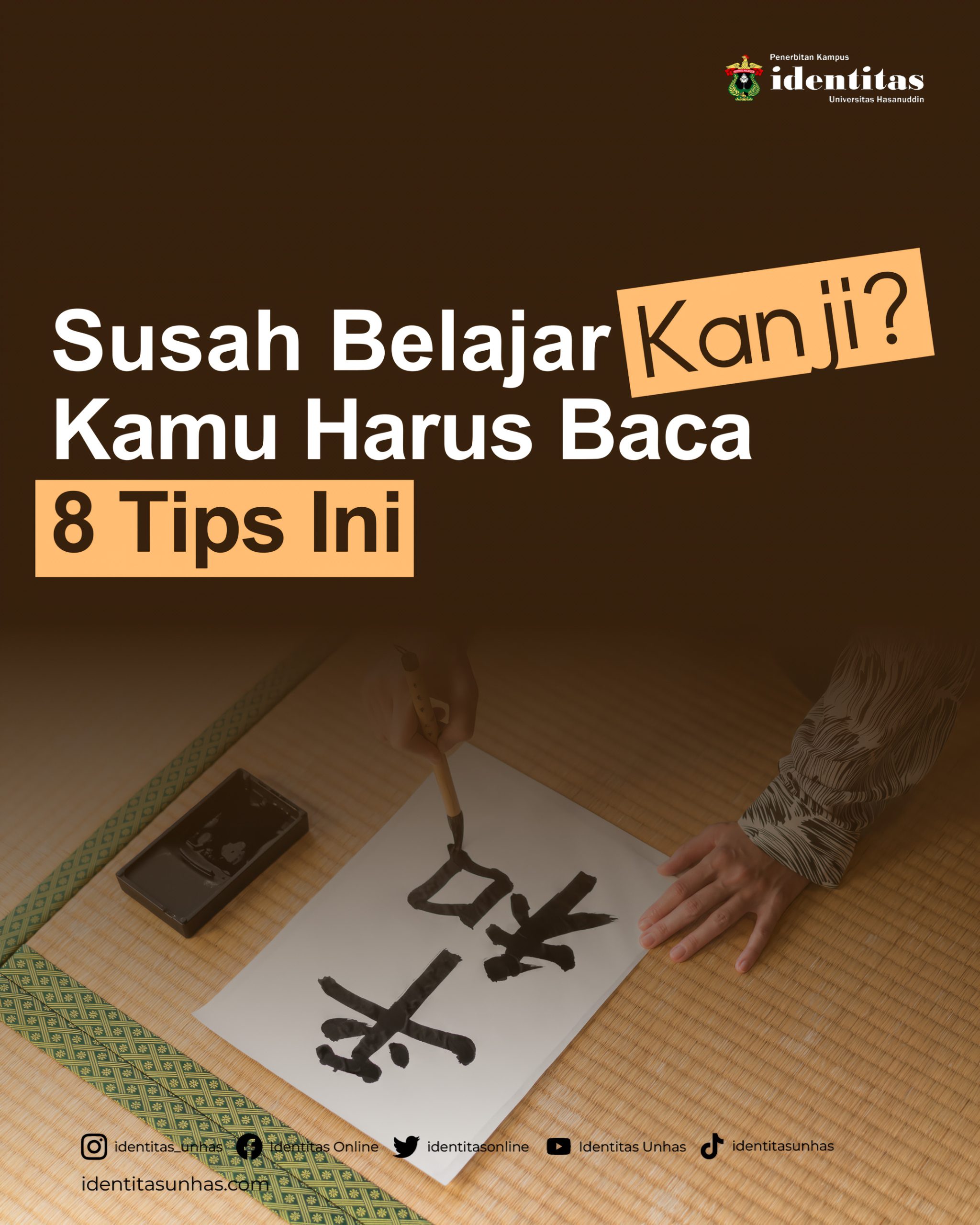Nama Citayam Fashion Week (CFW) akhir-akhir ini menjadi ramai dibincangkan di berbagai media. Aksi ini menjadi trending setelah warga beramai-ramai mengunjungi zebra cross di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, untuk saling memperagakan busana.
Sesuai namanya, fenomena ini awalnya diinisiasi oleh sekelompok pemuda asal Citayam yang kerap bercengkrama di area itu. Setelah viral, warga dari berbagai kalangan, bahkan selebriti papan atas, dan politisi pun ikut meramaikan ajang tersebut.
Viralnya aksi ini kemudian juga membuat warga di berbagai daerah di tanah air turut melakukan hal serupa. Di sisi lain, pemerintah kota Jakarta harus berpikir keras bagaimana mengelola kegiatan ini kedepannya.
Lantas, bagaimana pandangan ahli soal fenomena ini? Bagaimana fenomena ini muncul di masyarakat? Apa-apa saja dampak yang ditimbulkan? Dan apakah fenomena ini merupakan latah kultur? Untuk menjawab beberapa hal tersebut, reporter identitas Unhas, Zidan Patrio, melakukan wawancara dengan Budayawan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Dr Andi Faisal S S M Hum, Senin (1/8). Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana Anda melihat fenomena Citayam Fashion Week ini?
Ada banyak hal yang bisa kita lihat di sini. Mereka adalah anak muda yang butuh ruang mengekspresikan diri dan kebetulan menemukan momentumnya di dunia fesyen, kemudian menjadikan wilayah Dukuh Atas itu sebagai ajang untuk mengekspresikan identitasnya lewat pakaian.
Bagaimana fenomena seperti ini muncul dan berkembang di masyarakat?
Sebenarnya ini bukan fenomena baru. Misalnya di Jepang di tahun-tahun 90-an kita mendengar istilah Harajuku Fashion Street yang juga berangkat dari para remaja. Ini kemudian menginspirasi banyak orang terutama kalangan elit saat itu. Saya kira fenomena CFW ini tidak jauh dari itu. Jadi ada ruang-ruang yang mereka tidak merasa bebas, entah itu di lingkungan sekolah, keluarga, atau masyarakat secara umum. Nah, kemudian mereka mendapatkan ruangnya di situ. Mereka merasa bebas mengekspresikan diri lewat pakaian dan berbagai macam hal. Jadi dari segi budaya, itu menjadi bagian dari apa yang disebut sub-culture, budaya yang lebih rendah daripada yang dominan, karena mereka sulit mengakses budaya yang dominan itu. Jadinya mereka berekspresi sesuai selera mereka.
Jadi bisa dibilang bahwa CFW ini sebagai artikulasi kultural dari kelas bawah, begitu ya?
Saya melihatnya seperti itu. Karena memang kebanyakan dari mereka bukan dari kelompok elit. Mereka adalah para remaja yang secara ekonomi mungkin tidak bisa masuk ke dalam kelas-kelas atas, tapi mereka menunjukkan bahwa “kami juga bisa hadir di dunia fesyen”. Kita tahu bahwa fesyen itu identik dengan orang kaya yang ditunjukkan lewat pakaian-pakaian mahal. Mungkin kalau dalam bahasa Prancis istilahnya haute couture atau adibusana. Persoalannya, adibusana hanya bisa ditiru oleh orang mapan. Anak-anak muda ini tidak dapat menggapai itu dan justru menemukan ruangnya di CFW. Mereka menunjukkan bahwa dirinya juga punya selera fesyen tersendiri yang membedakan mereka dengan kelompok yang lebih elit secara ekonomi.
Apa dampak positif dan negatif dari adanya fenomena ini?
Dari segi positifnya ada banyak sebenarnya. CFW ini banyak melahirkan ide-ide baru soal apa sih sebenarnya fesyen itu, dan bahwa fesyen bisa menjadi milik semua orang dan tidak bisa diklaim oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Tapi (dampak negatifnya) melihat perdebatan akhir-akhir ini, memang ruangnya tidak tepat karena mereka melakukannya di jalan raya. Jadi menyebabkan kemacetan dan membuat masyarakat terganggu.
Apakah fenomena seperti ini sudah sering terjadi?
Ya, begitu. Fenomena ini bukan suatu hal yang baru. Di tahun 90-an, anak-anak muda di daerah Melawai Blok M melakukan pertunjukan fesyen seperti itu. Cuma semakin ke sini, sulit melihat bahwa gaya berpakaian yang dominan itu dipertanyakan lewat gaya anak berpakaian anak muda yang lebih bebas dan stylish. Saya kira juga yang baru ini adalah adanya media sosial yang turut mem-blow up fenomena itu. Sebelumnya kan belum ada medsos, jadi dengan kehadiran medsos itu juga menjadi bagian daripada viralnya fenomena tersebut.
Jika kita lihat di beberapa daerah lainnya juga mulai bermunculan fenomena serupa. Apakah ini berarti ada masalah kultur?
Ya, ini juga jadi gambaran bahwa ada yang belum beres di masyarakat kita terkait bagaimana mereka mengekspresikan diri secara bebas. Saya juga melihat mereka melakukan kritik terhadap kelompok-kelompok dominan yang tidak dapat mengakomodir nilai-nilai yang ada di masyarakat atau keluarga. Jadi mereka melakukan kritik secara kultural. Jadi pakaian itu kan juga bagian dari ekspresi budaya. Dengan itu mereka tunjukkan jati dirinya bahwa kita juga bisa hadir selain daripada kelompok-kelompok yang dominan seperti itu.
Menurut Anda, apakah ada sisi kreatifnya dari kegiatan ini?
Tentu saja ada kreatifitasnya di situ. Ini sebenarnya sudah bercampur baur antara kreativitas dengan ajang untuk memperlihatkan identitas diri mereka. Kita tahu bahwa anak muda itu ekspresif yang cenderung menunjukkan jati dirinya. Tapi dari sini saya sebenarnya lebih melihat kenapa mereka memilih jalanan. Itu kelihatan bahwa selama ini jalanan lebih dimiliki oleh kelompok-kelompok pemodal, penguasa, perkantoran. Maksudnya dikuasai kalangan atas. Tidak adanya ruang untuk mengekspresikan diri mereka membuat mereka berpikir bahwa jalanan juga jadi milik kami. Hampir semua ruang telah dianggap menjadi bagian kelompok pemilik modal. Bahkan secara perlahan-lahan beberapa artis memprivatisasi bahwa itu milik mereka secara hukum. Itu artinya ruang-ruang publik kita semakin sempit dan diprivatkan oleh berbagai macam kepentingan pemilik modal.
Dengan viralnya kegiatan ini, apakah ada kemungkinan busana di ajang CFW bisa jadi mode pakaian baru di masyarakat?
Tentu bisa. Mode kan tidak selamanya berasal dari kalangan elit. Memang selama ini nampak bahwa perkembangan fesyen itu merambah dari kalangan atas ke bawa. Tapi saya kira, mode kalangan bawa juga bisa menjadi sumber inspirasi bagi para desainer. Seperti kasus Harajuku Fashion Street misalnya. Atau bahkan misalnya pakaian-pakaian jins yang berasal dari kalangan pekerja atau buruh sebenarnya, yang kemudian menginspirasi desainer untuk membuat fesyen yang lebih bisa diterima secara umum. Jadi bisa timbal balik ya, bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas.
CFW ini memperlihatkan laki-laki yang berbusana layaknya perempuan dan disebut dapat menjadi bibit-bibit untuk hal berbau LGBT. Itu menurut Anda bagaimana?
Bisa saja itu ada, ya. Tapi saya tidak ingin melihatnya secara agama atau bertentangan dengan budaya tertentu. Saya hanya ingin melihat bahwa ruang publik itu bisa menjadi milik semua orang, termasuk jalanan. Setiap orang bebas berekspresi di ruang publik, yang tentu saja tetap menghormati aturan pemerintah. Jadi saya kira perlu ada regulasinya saja yang dibuat atau ruang yang disediakan untuk mereka mengekspresikan diri, entah mereka dari kelompok LGBT atau bukan itu tidak jadi masalah menurut saya.
CFW pada akhirnya harus dibubarkan karena beberapa alasan. Itu mendapat respons negatif dari pemuda di lokasi itu, yang kemudian melakukan tindakan anarkis. Bagaimana seharusnya pemerintah bersikap?
Yang namanya ekspresi diri kan tidak boleh ditahan, tapi harus disalurkan ke arah yang lebih terarah. Tentu saja anarkisme kita tidak tolerir, tetapi pemerintah juga perlu memberikan ruang atau alternatif ketika anak muda ingin mengekspresikan diri misalnya lewat pakaian, entah itu dengan memindahkan tempatnya atau membuat regulasi, misalnya ada Car free Day di situ, saya kira itu harus dipikirkan pemerintah. Terkait ide-ide kreatif mereka yang dihentikan saya tidak sepakat dengan itu.
Sebagai seorang akademisi, bagaimana cara menyikapi fenomena seperti ini, kapan kita harus mendukung, dan kapan harus menolak?
Dari satu sisi, saya mendukung selama itu menjadi ruang untuk mengekspresikan diri mereka secara kreatif. Tapi kalo sudah mengarah ke hal negatif misalnya anarkisme, itu harus kita hindari. Jika ruang-ruang itu bisa untuk melahirkan gagasan baru, misalnya, terkait fesyen, saya kira itu justru menarik.
Bagaimana harapan Anda untuk fenomena ini kedepannya?
Saya harap fenomena ini bisa menular ke tempat-tempat lain. Ini kan menjadi ajang untuk kreatifitas anak-anak muda. Saya kira di Makassar, misalnya, bisa diadakan atau tempat-tempat lain yang diharapkan bisa memunculkan ide-ide baru dalam hal desain yang sekaligus menegaskan bahwa mode bukan lagi milik kalangan atas saja, tetapi juga kalangan bawah.
Identitas narasumber:
Nama: Dr Andi Faisal S S M Hum
Jabatan Saat ini: Ketua Program Studi Magister Kajian Budaya (Cultural Studies) FIB Unhas
Riwayat Pendidikan:
S1: Sastra Perancis Univ. Hasanuddin, Makassar
S2: Kajian Budaya (Cultural Studies) Univ. Indonesia, Depok
S3: Kajian Budaya dan Media (Media and Cultural Studies) Univ. Gadjah Mada, Yogyakarta