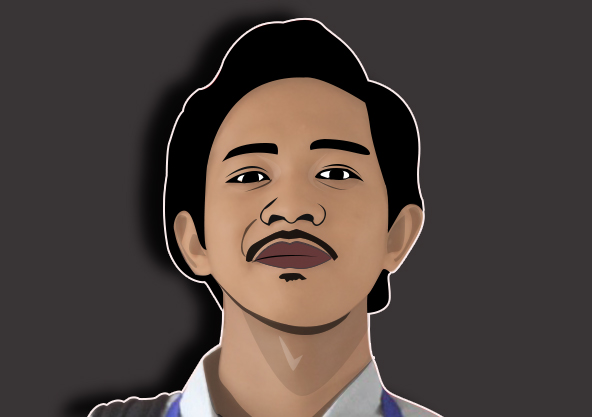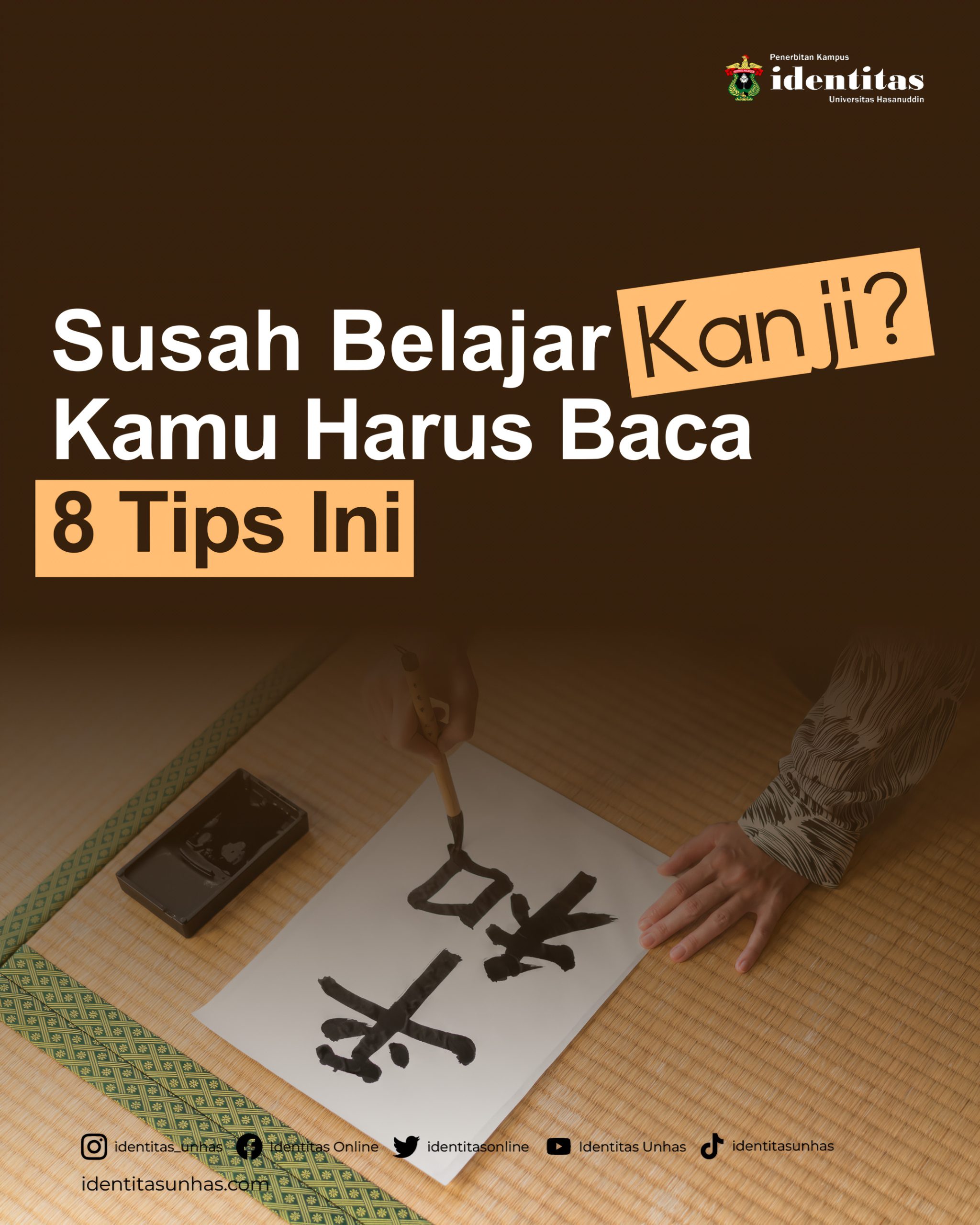Menurut World Health Organization (WHO), difabel merupakan suatu kehilangan atau ketidaknormalan, baik psikologis maupun fisiologis. Istilah difabel merupakan hal baru yang digagas untuk menggantikan istilah ‘penyandang cacat’, rupanya masih menjadi istilah yang tidak banyak diketahui masyarakat awam. Padahal istilah ini digunakan untuk merekonstruksi pemahaman awal yang memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan seseorang. Pada dasarnya masyarakat difabel tetaplah bagian dari masyarakat secara umum, yang memiliki kondisi fisik berbeda dengan kemampuan untuk melakukan hal yang sama melalui cara dan tingkat pencapaian yang berbeda pula.
Di Indonesia, penyandang difabel seringkali menghadapi berbagai perlakuan yang tidak manusiawi dari tataran keluarga hingga masyarakat. Keberadaan mereka dianggap sebagai aib bagi keluarga. Di sisi lain, dari sudut pandang moralitas nampaknya sedikit salah kaprah dengan memberi citra bagi mereka untuk dikasihani bahkan menjadi alat atau jembatan menuju surga. Selain itu, secara umum paradigma yang terbangun dalam masyarakat selama ini bahwa difabel sama sekali tidak mampu berperan dalam masyarakat, sehingga lingkungan sosial yang terbentuk pun tidak dapat diakses bagi mereka.
Secara umum, sudah cukup tersedia baik pada tataran konstitusional maupun peraturan perundang-undangan di pusat. Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan bahwa “seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”, artinya bahwa ada persamaan hak bagi setiap warga negara, tanpa membedakan kondisi fisik. Selain itu, pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa, “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Artinya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas pelayanan umum yang memadai bagi masyarakat, tak terkecuali bagi penyandang difabel.
Jika ditinjau dari pemikiran Paulo Freire dengan tema pokok Pendidikan Kritisnya, pada dasarnya mengacu pada landasan bahwa pemberdayaan adalah ‘proses memanusiakan manusia’. Gagasan ini berangkat dari suatu analisis bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya membuat masyarakat mengalami proses ‘dehumanisasi’. Maka dari itu, Pemberdayaan haruslah berlandaskan pada prinsip kemanusiaan tanpa mengenyampingkan hal minoritas.
Masalah Pendidikan difabel termasuk bias model pembangunan yang tidak peka dan diskriminatif terhadap masyarakat difabel dikaji dengan refleksi kritis. Bangunan sekolah maupun kampus belum sepenuhnya memudahkan terhadap masyarakat difabel. Model pembangunan yang mementingkan publik tanpa memperhatikan minoritas. Model pembangunan seperti ini terjadi di awal masa pembangunan tahun 70 dan 80-an. Seperti kampus pada umumnya dimana Gedung-gedung yang dibangun tahun tersebut belum menyediakan fasilitas untuk difabel. Baru kemudian tahun 2000-an beberapa gedung-gedung ada yang memiliki fasilitas bagi difabel.
Tugas utama Pendidikan adalah menciptakan ruang bagi sikap kritis terhadap sistem dan struktur yang diskriminatif terhadap penyandang difabel, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang sensitif dan non diskriminatif. Pendidikan sebagai bagian dari sistem masyarakat justru menjadi pelanggeng proses dehumanisasi akibat diskriminasi tersebut. Meminjam analisis Freire, proses kesadaran masyarakat terhadap difabel adalah akibat dari pandangan hidup masyarakat. Freire menggolongkan kesadaran disabilitas menjadi: kesadaran magis, kesadaran naif dan kesadaran kritis.
Lebih lanjutnya, Keasadaran kritis membuat individu mampu melakukan analisis terhadap suatu permasalahan yang terjadi secara holistis dan makro, sehingga dapat menguraikan sebab-akibat dari suatu permasalahan. Penguraian tersebut dapat memandang kelompok mana yang diuntungkan serta kelompok mana yang dirugikan. Kesadaran kritis yang dimiliki oleh manusia dapat menganggap sebagai subjek, yang tidak hanya mencari solusi sederhana tetapi juga berisiko tidak memanusiakan dirinya. Proses menumbuhkan kesadaran kritis bagi masyarakat dan difabel haruslah tertanam dalam ranah pendidikan, baik Pendidikan dasar, menengah, maupun Pendidikan tinggi.
Kesadaran kritis yang muncul akan menimbulkan bentuk kepedulian, yang selanjutnya pemberdayaan difabel merupakan sesuatu hal yang mendesak. Proses pemberdayaan difabel sendiri merupakan arena perjuangan kultural dan politik. Upaya pembebasan dari stereotip atau pandangan buruk dari masyarakat umum diperjuangankan melalui berbagai komunitas atau organisasi. Kesadaran masyarakat akan pandangannya terhadap difabel masih perlu dipertanyakan. Masyarakat difabel dalam berbagai ranah kehidupan seperti pendidikan, politik, sosial dan budaya, tetap berjuang dalam perwujudan kesetaraan sebagai manusia.
Penulis : Muh Nawir
Staf Penyunting PK identitas Unhas 2018,
Mahasiswa Departemen Ilmu Pemerintahan, FISIP Unhas
Angkatan 2015.